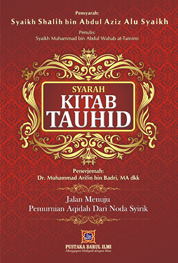Makna iman yang benar menurut Ahlussunnah wal jama’ah yaitu bahwasanya iman adalah keyakinan hati, perkataan lisan, dan amalan perbuatan. Iman bisa bertambah dengan sebab ketaatan dan bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan. Dalam masalah iman ini, terdapat dua paham pokok yang menyimpang[1] :
Pertama. Paham Wa’idiyyah
Yang memiliki pemahaman ini adalah Khawarij dan Mu’tazilah. Mereka berkeyakinan bahwa tidaklah dikatakan beriman kecuali orang yang membenarkan dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya, dan melaksanakan seluruh kewajiban serta meninggalkan seluruh dosa-dosa besar. Sehingga pelaku dosa besar menurut mereka bukanlah seorang mukmin.
Khawarij dan Mu’tazilah berbeda pendapat tentang hukum bagi pelaku dosa besar di dunia. Khawarij berpendapat bahwa pelaku dosa besar hukumnya kafir serta halal darah dan hartanya. Sementara Mu’tazilah berpendapat bahwa hukum pelaku dosa besar telah keluar dari makna iman namun belum masuk dalam kekafiran. Dalam istilah mereka disebut manzilah baina manzilatain, yakni keadaan di antara dua keadaan (iman dan kufur). Namun keduanya sepakat bahwa barangsiapa yang melakukan dosa besar dan belum bertaubat sampai meninggalnya maka orang tersebut kekal di neraka.
Kedua. Paham Murji’ah
Yaitu keyakinan bahwasanya iman cukup dengan pembenaran hati saja. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang tidak mengurangi keimanannya. Pelaku dosa besar menurut mereka tetap merupakan seorang mukmin yang sempurna imannya, sehingga tidak berhak untuk masuk neraka.
Oleh karena itu menurut mereka bahwa keimanan seseorang itu tidak bertambah dan tidak berkurang, karena iman cukup dengan pembenaran hati saja. Seluruh manusia memiliki keimanan yang sama dalam hatinya. Manusia yang beribadah sepanjang siang dan malam sama dengan manusia yang bermaksiat kepada Allah sepanjang siang dan malam, selama maksiatnya tersebut bukan kemaksiatan yang mengeluarkannya dari Islam.
Yang memiliki pemahaman Murji’ah ada empat kelompok[2] :
- Paham yang meyatakan bahwa iman adalah perkataan lisan saja. Ini merupakan pendapat Karromiyyah.
- Paham yang menyatakan bahwa iman adalah pembenaran dengan hati saja, meskipun tidak diucapkan. Ini merupakan pendapat ‘Asyaa’irah.
- Paham yang meyatakan bahwa iman cukup dengan pengenalan hati saja meskipun tidak membenarkannya. Jika seseorang sudah mengenal dengan hatinya meskipun tidak membenarkannya maka sudah dianggap seorang mukmin. Ini merupakan pendapat Jahmiyyah yang merupakan paham Murji’ah yang paling sesat.
- Paham yang menyatakan bahwa iman adalah ucapan lisan dan keyakinan hati. Ini pemdapat Murji’ah yang paling ringan sesatnya, yang disebut dengan murjiatul fuqaha.
Pelaku Dosa Besar Tetap Seorang Mukmin
Penyimpangan kedua kelompok di atas berimbas pada status keimanan seseorang. Menurut paham wa’idiyyah, pelaku dosa besar bukanlah seorang mukmin. Sedangkan menurut murji’ah, perbuatan dosa tidak mengurangi status kesempurnaan iman seseorang.
Adapun yang benar, seorang mukmin yang melakukan perbuatan dosa yang tidak sampai derajat kekafiran tetap dihukumi sebagai seorang mukmin, namun tidak sempurna imannya. Inilah mahdzab ahlus sunnah wal jama’ah. Di antara dalilnya yaitu ayat qishas dalam firman Allah Ta’ala:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik” (Al Baqarah:178).
Meskipun telah membunuh, mereka tetap dianggap saudara seiman. Allah juga berfirman :
وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى اْلأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {9} إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ … {10}
“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu” (Al Hujurat:9-10).
Dalam ayat ini Allah menyifati dua kelompok yang berperang dengan predikat mukmin walaupun mereka saling berperang. Allah juga memberitakan bahwa mereka adalah saudara, dan persaudaraan tidaklah terwujud kecuali antara sesama kaum mukminin, bukan antara mukmin dan kafir.
Orang-orang fasik yang berbuat kemaksiatan, keimanan mereka tidak hilang secara total Dalil-dalil syariat terkadang menetapkan keimanan pada mereka, seperti firman Allah :
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
“(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya (budak) yang beriman” (An Nisaa’:92).
Budak beriman yang dimaksud termasuk juga budak yang fasik. Terkadang juga dalil-dalil syariat menafikan keimanan pada mereka, seperti dalam hadits:
لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
“Seorang mukmin tidak disebut mukmin saat ia berzina” (H.R. Muslim 57)
Madzab ahlussunnah dalam menyikapi pelaku maksiat adalah tidak mengkafirkannya, namun juga tidak memutlakkan kesempurnaa iman pada diri mereka. Oleh akarena itu kita katakan sebagaimana penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah: “ Mereka (orang-orang fasik/pelaku dosa besar) adalah mukmin dengan keimanan yang kurang (tidak sempurna), atau bisa juga dikatakan mukmin dengan keimanannya dan fasik dengan dosa besarnya. Mereka tidak mendapat predikat iman secara mutlak (total), tidak pula hilang keimanan (secara total) dengan dosa besarnya”[3]
Penulis : dr. Adika Mianoki
1 Lihat Syarh Al ‘Aqidah Al Wasithiyah oleh Syaikh Khalil Harras 224-225 dan Syaikh ‘Utsaimin 448
2 Duruus min Al Qur’anul Kariim 133
3 Matan Al ‘Aqidah Al Washitiyyah