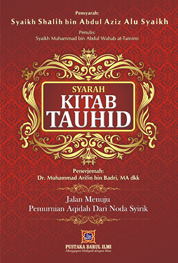Keyakinan yang benar seorang muslim terhadap nama dan sifat Allah adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: “Termasuk keimanan kepada Allah adalah beriman terhadap sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk diri-Nya dan Rasulullah tetapkan untuk Allah tanpa melakukan tahrif, ta’thil, tamtsil, dan takyif “ (Al ‘Aqidah Al Wasitiyyah).
Dalam menetapkan sifat Allah kita tidak boleh melakukan tahrif, ta’thil, tamtsil, dan takyif. Apa yang dimaksud dengan keempat hal tersebut? Berikut penjelasannya :
Pertama: Tahrif
Tahrif artinya mengubah, baik mengubah lafaz maupun makna. Namun yang banyak terjadi adalah tahrif makna. Pelaku tahrif disebut muharrif.Tahrif ada dua macam ;
- Tahrif lafzi, yaitu mengubah suatu bentuk lafaz ke bentuk lainnya, baik dengan mengubah harakat, menambah kata atau haruf, maupun dengan menguranginya. Contoh tahrif lafdzi:
- Mengubah lafaz (اسْتَوَى) dalam firman Allah (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) dengan (اسْتَوَلى), yaitu dengan menambah satu huruf. Tujuannya adalah untuk menolak sifat istiwa’.
- Menambah kalimat dalam firman Allah (وَجَاء رَبُّكَ) menjadi (وَجَاء أمر رَبُّكَ). Tujuannya adalah untuk menolak sifat majii’ (datang) yang hakiki bagi Allah.
- Tahrif maknawi, yaitu mengubah suatu makna dari hakikatnya, dan menggantinya dengan makna lafaz lain. Seperti perkataan ahlul bid’ahyang mengartikan sifat rahmah dengan keinginan memberi nikmat, atau mengartikan sifat ghadab (marah) dengan keinginan untuk membalas. Maksudnya adalah untuk menolak sifat rahmah dan sifat ghadhab yang hakiki bagi Allah.
Sebagian ulama menjelaskan istilah tahrif dengan istilah ta’wil, dan pelakunya disebut muawwil. Namun penggunaan istilah ta’wil kurang tepat, yang lebih tepat adalah tahrif. Di antara alasannya adalah :
- Penggunaan istilah tahrif sesuai dengan yang ada dalam Al Qur’an. lafaz yang terdapat dalam Al Qur’an adalah peniadaan tahrif, bukan ta’wil. Allah Ta’ala berfirman :يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ“Mereka mentahrif dari makna sesungguhnya“ (An Nisaa’:46). Ungkapan yang digunakan Al Qur’an tentu lebih utama dan lebih menunjukkan kepada makna yang dimaksud.
- Penggunaan istilah tahrif lebih tepat dan lebih adil. Orang yang melakukan ta’wil tanpa dalil tidak tepat jika dikatakan muawwil, namun lebih tepat disebut muharrif.
- Ta’wil yang tidak didasari dalil merupakan kebatilan, sehingga wajib menjauhkan hal tersebut dari manusia. Penggunaan istilah tahrif akan lebih membuat manusia takut dan meninggalkan perbuatan tersebut daripada penggunaan istilah ta’wil.
- Ta’wil tidak semuanya tercela. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: “Ya Allah, pahamkanlah dia ilmu agama dan ajarkanlah dia ta’wil (tafsir)“ . Allah Ta’ala juga berfirman :وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“Tidak ada yang mengetahui ta’wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya“ (Ali ‘Imran:7). Allah memuji orang-orang yang berilmu yang mengetahui tentang ta’wil. Ta’wil dalam ayat ini maksudnya adalah tafsir.
Berdasarkan alasan di atas, maka yang lebih tepat adalah penggunaan istilah tahrif daripada ta’wil. .Ahlussunah wal jama’ah mengimani nama dan sifat Allah tanpa disertai tahrif.
Kedua: Ta’thil
Ta’thil artinya mengosongkan dan meninggalkan. Maksudnya mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk diri-Nya, baik mengingkari keseluruhan maupun sebagian, baik dengan men-tahrif maknanya maupun menolaknya. Pelaku ta’thil disebut mu’atthil.
Walaupun nampak sama, terdapat perbedaan antara tahrif dan ta’thil. Tahrif menolak makna yang benar yang terdapat dalam nash dan menggantinya dengan makna yang tidak benar. Adapun ta’thil menolak makna yang benar namun tidak mengganti dengan makna lain, seperti perbuatan mufawwidhah. Maka dengan demikian setiap muharrif adalah mu’atthil, namun tidak setiap mu’atthil adalah muharrif.
Ketiga: Takyif
Takyif artinya menyebutkan tentang kaifiyah (karakteristik) suatu sifat. Takyif merupakan jawaban dari pertanyaan “bagaimana?”.
Ahlussnunnah wal jama’ah tidak men-takyif sifat Allah. Terdapat dalil naqli dan dalil ‘aqli yang menunjukkan larang takyif.
Dalil naqli, yaitu firman Allah Ta’ala :
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ
“Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) berkata tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui“ (Al A’raf:33).
Jika ada seseorang yang berkata : “Sesungguhnya Allah istiwa’ di atas ‘Arsy dengan cara demikian dan demikian (menyebutkan tata cara tertentu)”. Maka kita katakan orang tresebut telah berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu. Apakah Allah menjelaskan bahwa Dia istiwa’ dengan cara yang disebutkan tadi? Tidak. Allah memberitakan kepada kita bahwa Allah istiwa’ namun Allah tidak menjelaskan tentang tata cara istiwa’. Maka perbuatan orang tersebut termasuk takyif dan termasuk berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu.
Dalil yang lain yaitu firman Allah:
وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya “ (Al Isra’:36). Dalam ayat ini Allah melarang untuk mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu, termasuk dalam hal ini perbuatan takyif.
Terdapat pula dalil ‘aqli (metode akal) yang menunjukkan larangan takyif. Untuk mengetahui karakteristik sesuatau, harus melalui salah satu di antara tiga cara berikut:
- Melihat langsung sesuatu tersebut
- Melihat yang semisal dengan sesuatu tersebut
- Ada pemberitaan yang benar tentang sesuatu tersebut.
Kita tidak mengetahui zat Allah, atau yang semisal dengan zat Allah, begitu pula tidak ada yang memberitakan kepada kita tentang karakteristik zat Allah, sehingga kita tidak mungkin untuk men-takyif sifat-sifat Allah.
Catatan penting:
Yang dimaksud dengan menolak takyif bukan berati meniadakan kaifiyah dari sifat-sifat Allah. Kita tetap meyakini bahwa sifat-sifat Allah mempunyaikaifiyah, namun kita tidak mengetahui kaifiyah tersebut. Istiwa’ Allah di atas ‘Arsy tidak diragukan lagi pasti mempunyai kaifiyah tertentu, akan tetapi kita tidak mengetahuinya. Begitu pula sifat nuzul bagi Allah mempunyai kaifiyah tertentu, akan tetapi kita tiddak mengetahuinya. Segala sesuatu yang ada pasti mempunyai kaifiyah, namun ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui.
Faidah :
Terdapat perkataan yang populer yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang firman Allah: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (Ar Rahman istiwa’ di atas ‘Arsy) . Bagaimanakah Allah istiwa?. Beliau rahimahullah menjawab :
الاسْتِواءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالإيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ
“Sifat istiwa’ maknanya diketahui, kaifiyahnya tidak diketahui, mengimaninya wajib, bertanya tentang kaifiyahnya termasuk perbuatan bid’ah,“
Perkataan beliau (الاسْتِواءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ) artinya makna isiwa’ maklum (diketahui), yakni diketahui maknanya dalam bahasa Arab.
Perkataan beliau (وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ) maksudnya bahwa kaifiyah istiwa’ Allah tidak diketahui, karena tidak bisa dijangkau oleh akal. Jika dalil naqli dan akal meniadakan untuk mengetahui kaifiyah, maka wajib untuk tidak membicarakan kaifiyah sifat istiwa’ Allah.
Perkataan beliau (وَالإيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ) maksudnya adalah beriman dengan sifat tersebut. Karena Allah sendiri yang memberitakan, maka wajib untuk membenarkannya.
Perkataan beliau (وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ) maksudnya bertanya tentang kaifiyah istiwa’ adalah termasuk perbuatan bid’ah. Hal ini karena para sahabat yang lebih bersemangat untuk mengenal Allah tidak pernah bertanya hal tersebut.
Perkataan Imam Malik rahimahullah di atas merupakan kaidah yang berlaku bagi seluruh sifat-sifat Allah.
Keempat: Tamtsil
Tamtsil adalah menyebutkan sesuatu dengan yang semisalnya. Takyif dan tamtsil mempunyai makna yang hampir sama, namun terdapat perbedaan. Takyif lebih umum daripada tamtsil. Setiap mumatstsil adalah mukayyif, namun tidak setiap mukayyif adalah mumatstsil. Takyif adalah menyebutkan bentuk sesuatu tanpa menyebutkan contohnya. Misalnya seseorang mengatakan bahwa pena miliknya bentuknya demikian dan demikian (tanpa menyebutkan contoh). Jika dia menyebutkan contohnya, maka dia melakukan tamtsil. Misalnya mengatakan bahwa pena miliknya serupa dengan pena milik si A.
Yang dimaksud tamtsil dalam asma’ wa shifat adalah menyamakan nama dan sifat Allah dengan makhluk. Sebagian ulama ada yang menggolongkantamtsil termasuk takyif muqayyad. Takyif ada dua bentuk: takyif mutlaq (takyif) dan takyif muqayyad (tamtsil)
Perbuatan tamtsil terlarang dalam nama dan sifat Allah karena banyak dalil yang melarang tamtsil, seperti firman Allah dalam surat As Syuura 11, Maryam 65, dan Al Ikhlas 4. Secara akal juga tamtsil tidak bisa diterima karena alasan-alasan berikut:
- Tidak mungkin ada persamaan antara Allah dengan makhluk dalam segala sisi. Seandainya tidak ada perbedaan di antara Allah dan makhluk kecuali dalam perbedaan wujud, niscaya itupun sudah cukup. Wujudnya Allah adalah wajib, sedangkan wujudnya makhluk diawali dengan ketidakadaan dan akan berakhir. Jika wujudnya saja berbeda, maka lebih-lebih lagi perbedaan dalam nama dan sifat.
- Terdapat perbedaan yang sangat jauh antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Sifat as sam’u mislanya. Pendengaran Allah sangat sempurna, sedangkan makhluk sangat terbatas.
- Zat Allah berbeda dengan makhluk, maka sifat-sifatnya pun berbeda. Karena sifat selalu menyertai zat.
- Di antara para makhluk saja terdapat perbedaan satu dengan yang lainnya. Bahkan makhluk yang jenisnya sama pun memiliki sifat yang berbeda, Tentu saja lebih-lebih lagi perbedan antara makhluk dengan Zat yang menciptakan mereka.
Sebagian ulama menjelaskan istilah tamtsil dengan menggunakan istilah tasybih, dan pelakunya disebut musyabbih. Namun penggunaan istilahtasybih kurang tepat, yang lebih tepat adalah tamtsil Di antara alasannya adalah:
- Penggunaan istilah tamtsil sesuai dengan yang ada dalam Al Qur’an. lafaz yang terdapat dalam Al Qur’an adalah peniadaan tamtsil, bukantasybih. Allah Ta’ala berfirman:لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat“ (Asy Syuura:11). Ungkapan yang digunakan Al Qur’an lebih utama dan lebih menunjukkan kepada makna yang dimaksud.
- Makna tasybih menurut sebagian kelompok maksudnya adalah penetapan sifat. Oleh karena itu, mereka menggelari Ahlussunnah yang mentepakan sifat dengan musyabbihah. Sehingga terkadang makna tasybih dimaknai dengan sesuatu yang keliru.
- Penafian tasybih secara mutlak tidak tepat. Karena di antara dua zat atau sifat yang berbeda pasti memiliki sisi kesamaan. Sisi kesamaan ini termasuk bagian dari tasybih.
Faidah:
Tasybih ada dua bentuk :
- Tasybih Al Makhluq bil Khaaliq (menyerupakan makhluk dengan pencipta). Maksudnya menetapkan sesuatu bagi makhluk yang merupakan kekhususan Allah dalam perbuatan-Nya, hak untuk diibadahi, dan dalam sifat-Nya. Dalam perbuatan-Nya, seperti orang yang berbuat syirikdalam rububiyah, yakni meyakini bahwa ada pencipta selain Allah. Dalam hak-Nya, misalnya perbuatan orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka, di mana mereka meyakini bahwa berhala-berhala tersebut mempunyai hak untuk disembah. Dalam sifat Allah, misalnya orang-orang yang berlebihan dalam memuji Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan pujian yang khusus bagi Allah.
- Tasybih Al Khaaliq bil Makhluq (menyerupakan pencipta dengan makhluk). Maksudnya menetapkan bagi zat maupun sifat Allah berupa kekhususan seperti yang ada pada makhluk. Seperti ungkapan bahwa tangan Allah sama dengan tangan makhluk, istiwa’ Allah sama denganistiwa’ pada makhluk, Allah memiliki anak, dan lain-lain.
Referensi
- Syarh Al ‘Aqidah Al Wasithiyyah karya Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan hafidzahullah
- Syarh Al ‘Aqidah Al Wasithiyyah karya Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah
- Fathu Rabbil Bariyyah bi Talkhis Al Hamawiyyah karya Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah
Penyusun : dr. Adika Mianoki