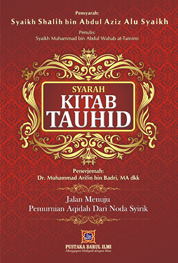al-Fairuz Abadi mengatakan tentang makna “وَسَّلَ إِلَى اللهِ تَوْسِيْلاً”: “Yaitu ia mengamalkan suatu amalan yang dengannya ia dapat mendekatkan diri kepada Allâh,”[2]
Selain itu wasilah juga mempunyai makna yang lain yaitu kedudukan di sisi raja, derajat dan kedekatan.[3]
Wasilah secara syar’i (terminologi) yaitu yang diperintahkan di dalam al-Qur'ân adalah segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allâh Azza wa Jalla , yaitu berupa amal ketaatan yang disyari’atkan.
Allâh Azza wa Jalla berfirman :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allâh dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, [al-Mâ-idah/5:35]
Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhu berkata, “Makna wasilah dalam ayat tersebut adalah peribadahan yang dapat mendekatkan diri kepada Allâh (al-Qurbah).” Demikian pula yang diriwayatkan dari Mujâhid, Abu Wa’il, al-Hasan, ‘Abdullah bin Katsir, as-Suddi, Ibnu Zaid dan yang lainnya. Qatâdah berkata tentang makna ayat tersebut, "Mendekatlah kepada Allâh dengan mentaati-Nya dan mengerjakan amalan yang diridhai-Nya.”[4]
Adapun tawassul (mendekatkan diri kepada Allâh dengan cara tertentu) ada tiga macam:
1. Masyrû’, yaitu tawassul kepada Allâh Azza wa Jalla dengan Asma’ dan Sifat-Nya dengan amal shalih yang dikerjakannya atau melalui doa orang shalih yang masih hidup.
2. Bid’ah, yaitu mendekatkan diri kepada Allâh Azza wa Jalla dengan cara yang tidak disebutkan dalam syari’at, seperti tawassul dengan pribadi para Nabi dan orang-orang shalih, dengan kedudukan mereka, kehormatan mereka, dan sebagainya.
3. Syirik, bila menjadikan orang-orang yang sudah meninggal sebagai perantara dalam ibadah, termasuk berdoa kepada mereka, meminta keperluan dan memohon pertolongan kepada mereka.[5]
TAWASUL YANG MASYRU
Tawassul yang masyru’ (yang disyari’atkan) ada 3 macam, yaitu:[6]
1. Tawassul Dengan Nama-Nama Dan Sifat-Sifat Allâh Subhanahu Wa Ta’ala .
Yaitu seseorang memulai doa kepada Allâh Azza wa Jalla dengan mengagungkan, membesarkan, memuji, mensucikan Dzat-Nya yang Maha Tinggi, Nama-Nama-Nya yang indah dan sifat-sifat-Nya yang tinggi kemudian berdoa (memohon) apa yang dia inginkan. Inilah bentuk doa dengan menjadikan pujian dan pengagungan sebagai wasilah kepada-Nya agar Dia mengabulkan doa dan permintaannya sehingga dia pun mendapatkan apa yang dia minta dari Rabb-nya.
Dalil dari al-Qur-ân tentang tawassul yang masyru’ ini adalah firman Allâh Azza wa Jalla :
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Dan Allâh memiliki Asma-ul Husna (nama-nama yang terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asma-ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-nama-Nya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. [al-A’râf/7:180]
Dalil dari al-Hadits tentang tawassul yang masyru’ ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Mâlik Radhiyallahu anhu, bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendengar seseorang yang berucap dalam dalam shalatnya :
اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ، اَلْمَنَّانُ، يَا بَدِيْعَ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَاْلإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، إِنِّي أَسْأَلُكَ ( الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ )
“Ya Allâh, aku mohon kepada-Mu. Sesungguhnya bagi-Mu segala pujian, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Mu, Maha Pemberi nikmat, Pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Ya Rabb Yang memiliki keagungan dan kemuliaan, ya Rabb Yang Mahahidup, ya Rabb yang mengurusi segala sesuatu, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu agar dimasukkan (ke surga dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka).”
Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيْمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى
Sungguh dia telah meminta kepada Allâh dengan Nama-Nya yang paling agung yang apabila seseorang berdoa dengannya niscaya akan dikabulkan, dan apabila ia meminta akan dipenuhi permintaannya.”[7]
Juga hadits lain yang diriwayatkan dari Anas bin Mâlik, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdoa :
يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِى شَأْنِي كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.
Wahai Rabb Yang Mahahidup, wahai Rabb Yang Maha Berdiri sendiri (tidak butuh segala sesuatu) dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan Engkau serahkan urusanku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dari-Mu).[8]
2. Seorang Muslim Bertawassul Dengan Amal Shalih Yang Dilakukannya.
Allâh Azza wa Jalla berfirman :
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
(Yaitu) orang-orang yang berdoa: ‘Ya Rabb kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari adzab Neraka. [Ali ‘Imrân/3:16][9]
Dalil lainnya yaitu tentang kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua lalu mereka bertawassul kepada Allâh Azza wa Jalla dengan amal-amal mereka yang shalih lagi ikhlas, yang mereka tujukan untuk mengharap wajah Allâh Yang Mahamulia, maka mereka diselamatkan dari batu yang menutupi mulut gua tersebut.[10]
3. Tawassul Kepada Allâh Azza Wa Jalla Dengan Doa Orang Shalih Yang Masih Hidup.
Jika seorang Muslim menghadapi kesulitan atau tertimpa musibah besar, namun ia menyadari kekurangan-kekurangan dirinya di hadapan Allâh Azza wa Jalla , sedang ia ingin mendapatkan sebab yang kuat kepada Allâh, lalu ia pergi kepada orang yang diyakini keshalihan dan ketakwaannya, atau memiliki keutamaan dan pengetahuan tentang al-Qur-ân serta as-Sunnah, kemudian ia meminta kepada orang shalih itu agar mendoakan dirinya kepada Allâh supaya ia dibebaskan dari kesedihan dan kesusahan, maka cara demikian ini termasuk tawassul yang dibolehkan, seperti:
Pertama : Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Mâlik Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Pernah terjadi musim kemarau pada masa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam , yaitu ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhutbah di hari Jum’at. Tiba-tiba berdirilah seorang Arab Badui, ia berkata, ‘Wahai Rasûlullâh, telah musnah harta dan telah kelaparan keluarga.’ Lalu Rasûlullâh mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, ‘Ya Allâh turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allâh, turunkanlah hujan kepada kami.” Tidak lama kemudian turunlah hujan.[11]
Kedua : Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Mâlik Radhiyallahu anhu bahwa ‘Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu anhu -ketika terjadi musim paceklik- ia meminta hujan kepada Allâh Azza wa Jalla melalui ‘Abbas bin ‘Abdil Muthalib Radhiyallahu anhu, lalu berkata, “Ya Allâh, dahulu kami bertawassul kepada-Mu melalui Nabi kami, lalu Engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang kami memohon kepada-Mu melalui paman Nabi kami, maka berilah kami hujan.” Ia (Anas bin Mâlik) berkata, “Lalu mereka pun diberi hujan.”[12]
Seorang Mukmin dapat pula minta didoakan oleh saudaranya untuknya seperti ucapannya, “Berdoalah kepada Allâh agar Dia memberikan keselamatan bagiku atau memenuhi keperluanku.” Dan yang serupa dengan itu. Sebagaimana juga Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam meminta kepada seluruh ummatnya untuk mendoakan beliau, seperti bershalawat kepada beliau setelah adzan atau memohon kepada Allâh agar beliau diberikan wasilah, keutamaan dan kedudukan yang terpuji yang telah dijanjikan oleh-Nya.
Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash Radhiyallahu anhu, bahwasanya ia mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ تَعَالَى، وَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.
Apabila kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Kemudian bershalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya barang siapa yang bershalawat kepadaku sekali, maka Allâh akan bershalawat kepadanya sepuluh kali. Kemudian mohonkanlah wasilah (derajat di Surga) kepada Allâh untukku karena ia adalah kedudukan di dalam Surga yang tidak layak bagi seseorang kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allâh dan aku berharap akulah hamba tersebut. Maka, barang siapa memohonkan wasilah untukku, maka dihalalkan syafa’atku baginya.[13]
Doa yang dimaksud adalah doa sesudah adzan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :
اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ
Ya Allâh, Rabb Pemilik panggilan yang sempurna (adzan) ini dan shalat (wajib) yang akan didirikan. Berilah al-wasilah (kedudukan di Surga) dan keutamaan kepada Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam . Bangkitkanlah beliau sehingga dapat menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.[14]
TAWASSUL BID’AH
Tawassul yang bid’ah yaitu mendekatkan diri kepada Allâh dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Tawassul yang bid’ah ini ada beberapa macam,[15] di antaranya:
1. Tawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam atau kedudukan orang selainnya.
Perbuatan ini adalah bid’ah dan tidak boleh dilakukan. Adapun hadits yang berbunyi:
إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ بِجَاهِيْ، فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ
Jika kalian hendak memohon kepada Allâh, maka mohonlah kepada-Nya dengan kedudukanku, karena kedudukanku di sisi Allâh adalah agung
Hadits ini bathil tidak jelas asal-usulnya dan tidak terdapat sama sekali dalam kitab-kitab hadits yang menjadi rujukan, tidak juga seorang Ulama ahli hadits pun yang menyebutkannya sebagai hadits.[16] Jika tidak ada satu pun dalil yang shahih tentangnya, maka itu berarti tidak boleh, sebab setiap ibadah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan dalil yang shahih dan jelas.
2. Tawassul dengan dzat makhluk.
Jika dimaksudkan: seseorang bersumpah dengan makhluk dalam meminta kepada Allâh, maka tawassul ini—seperti bersumpah dengan makhluk—tidak dibolehkan, sebab sumpah makhluk terhadap makhluk tidak dibolehkan, bahkan termasuk syirik, sebagaimana disebutkan di dalam hadits, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ
Barang siapa yang bersumpah dengan selain Nama Allâh, maka ia telah berbuat kufur atau syirik[17]
Apalagi bersumpah dengan makhluk kepada Allâh, maka Allâh tidak menjadikan permohonan kepada makhluk sebagai sebab terkabulnya doa dan Dia tidak mensyari’atkannya.
3. Tawassul dengan hak makhluk.
Tawassul ini pun tidak dibolehkan, karena dua alasan:
Pertama, bahwa Allâh Azza wa Jalla tidak wajib memenuhi hak atas seseorang, tetapi justru sebaliknya, Allâh-lah yang menganugerahi hak tersebut kepada makhluk-Nya, sebagaimana firman-Nya :
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
“... Dan merupakan hak Kami untuk menolong orang-orang yang beriman.” [ar-Rûm/30:47]
Orang yang taat berhak mendapatkan balasan (kebaikan) dari Allâh karena anugerah dan nikmat, bukan karena balasan setara sebagaimana makhluk dengan makhluk yang lain.
Kedua, hak yang dianugerahkan Allâh kepada hamba-Nya adalah hak khusus bagi diri hamba tersebut dan tidak ada kaitannya dengan orang lain dalam hak tersebut. Jika ada yang bertawassul dengannya, padahal dia tidak mempunyai hak berarti dia bertawassul dengan perkara asing yang tidak ada kaitannya antara dirinya dengan hal tersebut dan itu tidak bermanfaat untuknya sama sekali.[18]
Adapun hadits yang berbunyi :
أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ ....
“Aku memohon kepada-Mu dengan hak orang-orang yang memohon ....”
Hadits ini dha’if sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (III/21), lafazh ini milik Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam sanad hadits ini terdapat ‘Athiyyah al-‘Aufi dari Abu Sa’id al-Khudri Radhiyallahu anhu . ‘Athiyyah adalah perawi yang dha’if seperti yang dikatakan oleh Imam an-Nawawi rahimahullah dalam al-Adzkâr, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam al-Qâ’idatul-Jalîlah dan Imam adz-Dzahabi dalam al-Miizân, bahkan dikatakan (dalam adh-Dhu’aa-faa’, I/88): “Disepakati kedha’ifannya!!” Demikian pula oleh al-Hafizh al-Haitsami di tempat lainnya dari Majma’uz Zawâ-id (V/236).[19]
TAWASSUL SYIRIK
Tawassul yang syirik, yaitu menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara dalam ibadah seperti berdoa kepada mereka, meminta hajat, atau memohon pertolongan sesuatu kepada mereka.
Allâh Azza wa Jalla berfirman :
أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ
Ingatlah! Hanya milik Allâh agama yang murni (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia (berkata): ‘Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allâh dengan sedekat-dekatnya.’ Sungguh, Allâh akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allâh tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. [az-Zumar/39:3][20]
Tawassul dengan meminta doa kepada orang mati tidak diperbolehkan bahkan perbuatan ini adalah syirik akbar. Karena mayit sudah tidak bias lagi berdoa seperti ketika ia masih hidup. Demikian juga meminta syafa’at kepada orang mati, karena ‘Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu anhu, Mu’awiyah bin Abi Sufyan Radhiyallahu anhu dan para Shahabat yang bersama mereka, juga para Tabi’in yang mengikuti mereka dengan baik ketika ditimpa kekeringan mereka memohon diturunkannya hujan, bertawassul, dan meminta syafa’at kepada orang yang masih hidup, seperti kepada al-‘Abbas bin ‘Abdil Muththalib dan Yazid bin al-Aswad. Mereka tidak bertawassul, meminta syafa’at dan memohon diturunkannya hujan melalui Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, baik di kuburan beliau atau pun di kuburan orang lain, tetapi mereka mencari pengganti (dengan orang yang masih hidup).
‘Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu anhu berkata, ‘Ya Allâh, dahulu kami bertawassul kepada-Mu dengan perantaraan Nabi-Mu, sehingga Engkau menurunkan hujan kepada kami dan kini kami bertawassul kepada-Mu dengan perantaraan paman Nabi kami, karena itu turunkanlah hujan kepada kami.’ Ia (Anas) berkata: ‘Lalu Allâh menurunkan hujan.’[21] Mereka menjadikan al-‘Abbas Radhiyallahu anhu sebagai pengganti dalam bertawassul ketika mereka tidak lagi bertawassul kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, sesuai dengan yang disyari’atkan sebagaimana yang telah mereka lakukan sebelumnya. Padahal sangat mungkin bagi mereka untuk datang ke kubur Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan bertawassul melalui beliau, jika memang hal itu dibolehkan. Dan mereka (para Sahabat) meninggalkan praktek-praktek tersebut merupakan bukti tidak diperbolehkannya bertawassul dengan orang mati, baik meminta doa maupun syafa’at kepada mereka. Seandainya meminta doa atau syafa’at, baik kepada orang mati atau maupun yang masih hidup itu sama saja, tentu mereka tidak berpaling dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada orang yang lebih rendah derajatnya.[22]
وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ
“Dan tidak (pula) sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allâh memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki dan engkau (Muhammad) tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.” [Fâthir/35:22]
Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas حَفِظَهُ الله تَعَالَى
[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 11/Tahun XV/1433H/2012M.]
_______
Footnote
[1]. Lihat an-Nihâyah fî Gharîbil Hadîts wal Atsar (V/185) oleh Majduddin Abu Sa’adat al-Mubarak Muhammad al-Jazry yang terkenal dengan Ibnul Atsir (wafat th. 606 H) rahimahullah.
[2]. Qâmûsul Muhîth (III/634), cet. Daarul Kutub Ilmiyah.
[3]. Tawassul Anwâa’uhu wa Ahkâmuhu (hlm. 12), oleh Syaikh al-Albani, cet. Maktabah al-Ma’arif, th. 1421 H.
[4]. Tafsîr Ibni Jarir ath-Thabari (IV/567), cet. Daarul Kutub al-’Ilmiyyah dan Tafsîr Ibni Katsiir (III/103), tahqiq Sami Muhammad as-Salamah, cet. IV, th. 1428 H, Daar at-Thaybah.
[5]. Mujmal Ushûl Ahlis Sunnah wal Jamâ’ah fil ‘Aqîdah (hlm. 15-17).
[6]. Diringkas dari at-Tawassul Anwâ’uhu wa Ahkâmuhu (hlm. 30-40), oleh Syaikh al-Albani; Majmû’ Fatâwâ wa Rasâ-il (II/335-355) oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin; dan Haqîqatut Tawassul al-Masyrû’ wal Mamnû’, tash-hih Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Jibrin.
[7]. Shahîh: HR. Abu Dawud (no. 1495), an-Nasa-i (III/52) dan Ibnu Majah (no. 3858), dari Sahabat Anas bin Mâlik Radhiyallahu anhu . Lihat Shahîh Ibni Mâjah (II/329).
[8]. Shahîh: HR. An-Nasa-i, al-Bazzar dan al-Hakim (I/545).Hadits ini hasan, lihat Shahîhut Targhîb wat Tarhîb (I/417, no. 661).
[9]. Lihat juga QS. Ali ‘Imran: 53 dan 193-194.
[10]. Shahîh: HR. al-Bukhari (no.2272, 3465) dan Muslim (no. 2743) dari Sahabat ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma. Lihat Riyâdhush Shâlihîn (no. 12, bab Ikhlas)
[11]. Shahîh: HR. al-Bukhari (no. 932, 933, 1013) dan Abu Dawud (no. 1174), dari Sahabat Anas bin Mâlik Radhiyallahu anhu .
[12]. Shahîh: HR. al-Bukhari (no. 1010, 3710) dan Ibnu Sa’d dalam ath-Thabaqât (III/20) cet. Daarul Fikr.
[13]. Shahîh: HR. Muslim (no. 384), Abu Dawud (no. 523), at-Tirmidzi (no. 3614) dan an-Nasa’i (II/25), lafazh ini milik Muslim.
[14]. Shahîh: HR. al-Bukhari (Fat-hul Bâri, II/94 no. 614),Abu Dawud (no. 529), at-Tirmidzi (no. 211), an-Nasa-i (II/26-27) dan Ibnu Majah (no. 722)
[15]. Dinukil dari ‘Aqîdatut Tauhîd (hlm. 142-144) oleh Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan.
[16]. Lihat Majmû’ Fatâwâ (I/319) oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.
[17]. Shahîh: HR. At-Tirmidzi (no. 1535) dan al-Hakim (I/18, IV/297), Ahmad (II/34, 69, 86) dari ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma. al-Hâkim berkata, “Hadits ini Shahîh menurut syarat al-Bukhari dan Muslim.” Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat juga Silsilatul Ahâdîts as-Shahîhah (no. 2042).
[18]. ‘Aqîdatut Tauhîd (hlm. 144).
[19]. Dinukil dari Tawassul ‘Anwâ-uhu wa Ahkâmuhu (hlm. 92) oleh Syaikh al-Albani. Lihat juga Silsilatul Ahâdîts adh-Dha’îfah (no.24) oleh Syaikh al-Albani.
[20]. Lihat juga QS. Al-Ahqâf: 5-6.
[21]. Shahîh: HR.Al-Bukhari (no.1010) dari Sahabat Anas.
[22]. Lihat ‘Aqiidatut Tauhiid (hlm.142-143).